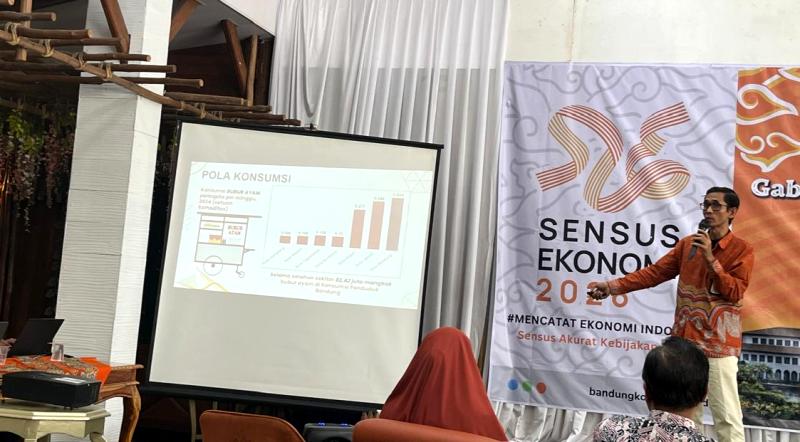Ketika “Rahvayana, Kala Cinta di Jabar” Menjadi Jamuan Para Elite
Oleh: Adhi M Sasono
Di penghujung tahun 2025, panggung Sabuga ITB berubah menjadi ruang perayaan yang tak biasa.
Drama musikal “Rahvayana: Kala Cinta di Jabar” hadir bukan sekadar sebagai tontonan seni, melainkan sebagai jamuan simbolik bagi para elite daerah.
Para bupati, wali kota, dan pejabat lintas eselon duduk berderet, menikmati sajian budaya yang dimainkan dengan penuh kelincahan oleh nama-nama besar: Sule, Tri Utami, Sujiwo Tejo, Marcell Siahaan, hingga Isyana Sarasvati.
Malam itu, tawa pecah. Senyum mengembang. Aroma wewangian menyelinap di sudut-sudut gedung. Berpadu dengan denting musik dan dialog jenaka yang sesekali menggigit.
Para abdi negara yang selama setahun bergelut dengan rapat, laporan, dan tuntutan publik akhirnya mendapat jeda.
Sebuah hiburan yang seolah dirancang untuk membahagiakan mereka, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras melayani masyarakat.
Pertunjukan ini memang bekerja dengan sangat baik. Komedi Sule mencairkan suasana, refleksi filosofis Sujiwo Tejo mengajak berpikir sambil tersenyum, dan kekuatan vokal para penyanyi membawa emosi naik-turun.
Para pejabat pun larut, tertawa lepas, seperti manusia biasa yang lupa sejenak pada jabatan dan protokol.
Namun di situlah letak ironi yang tak terucap.
Malam itu terasa seperti kisah klasik: raja menjamu para punggawanya yang baru pulang dari medan tugas.
Panggung menjadi singgasana, kursi penonton menjadi lambang mahkota dan gelang emas.
Jangan berharap rakyat biasa bisa duduk di sana. Pertunjukan ini bukan untuk mereka yang antre layanan publik.
Rasa Asing
Bukan untuk mereka yang mengeluh soal jalan rusak atau harga bahan pokok. Aksesnya jelas, hanya bagi mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
Rakyat, seperti biasa, cukup bahagia dari kejauhan. Mendengar sayup-sayup musik yang lolos dari celah gedung Sabuga.
Mungkin ada rasa bangga karena kesenian daerah dipentaskan megah.
Mungkin juga ada rasa asing, karena seni yang lahir dari rahim kebudayaan bersama justru dipersembahkan secara eksklusif.
Rahvayana malam itu sukses sebagai hiburan. Ia berhasil membahagiakan para elite, membuat mereka tertawa dan tersenyum di akhir tahun.
Tetapi pertunjukan ini juga menjadi cermin bahwa di negeri ini, bahkan kebahagiaan pun kadang memiliki pagar.
Seni yang seharusnya menjadi milik bersama, pada momen tertentu, berubah menjadi hak istimewa.
Dan ketika lampu panggung padam, para pejabat pulang dengan hati ringan. Sementara di luar gedung, rakyat tetap melanjutkan hidupnya, dengan atau tanpa drama musikal, menjadi penonton yang tak pernah benar-benar diundang ke dalam panggung kekuasaan. ***